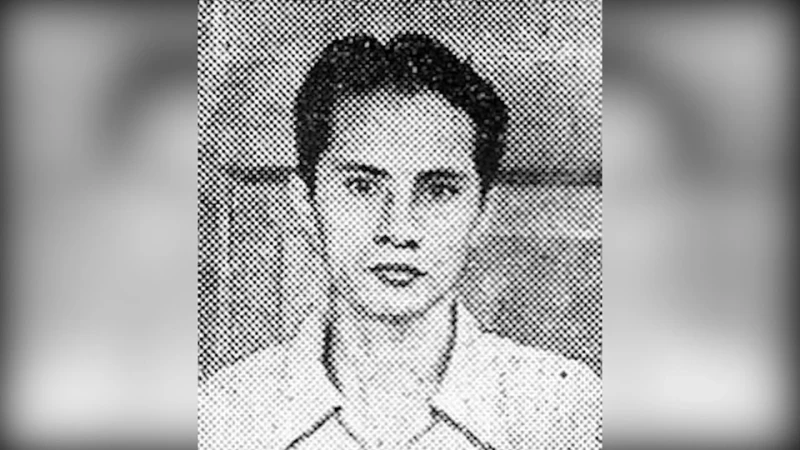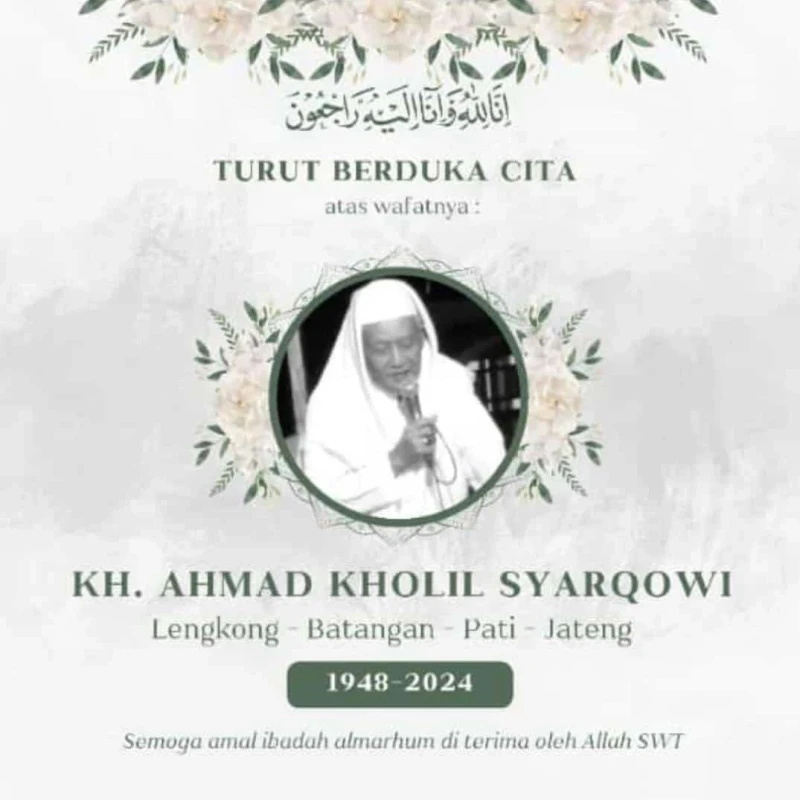Anas Ma’ruf: Aktivis Lesbumi, Sang Administrator Kebudayaan
Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:00 WIB
Selain nama-nama seperti Usmar Ismail, Asrul Sani, Djamaludin Malik, dan Mahbub Djunaidi, ada satu lagi tokoh yang menjadi aktivis generasi awal Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Anas Ma’ruf.
Ketika Nahdlatul Ulama (NU) berencana mendirikan Lesbumi, Usmar Ismail dan Asrul Sani mengusulkan Anas Ma’ruf sebagai sekretaris jenderal. Pilihan ini didasarkan pada keyakinan mereka terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Anas.
“Memang, di Indonesia, apalagi di kalangan kebudayaan dan kesenian, susah menemukan tenaga administrator seperti Anas yang cermat dan tak kenal lelah, tekun, dan selalu bersemangat,” ujar Ajip Rosidi dalam Buku Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari (2010: 192).
Di Lesbumi, Anas Ma’ruf turut membantu Asrul Sani mengelola Majalah Gelanggang, yang pertama kali diterbitkan pada Desember 1966 (No. 1 Tahun 1). Nama Gelanggang konon terinspirasi dari sebuah ruang atau tempat pertemuan kebudayaan yang sebelumnya hadir dalam rubrik mingguan Siasat. Asrul Sani, bersama Chairil Anwar dan Rivai Apin, pernah aktif sebagai pengasuh rubrik tersebut.
Kelahiran Sumatera Barat
Anas Ma'ruf lahir di Bukittinggi pada 27 Oktober 1922 dan wafat pada 17 Agustus 1980. Ia menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada periode 1946–1948. Anas pernah berkiprah sebagai redaktur di berbagai media, termasuk Berita Indonesia, Majalah Arena, Majalah Patriot, dan Majalah Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris BMKN dan menjadi dosen Kesusastraan Indonesia di Universitas Tokyo, Jepang.
Anas Ma'ruf mulai menulis sajak pada masa pendudukan Jepang. Selama masa Revolusi, ia tidak hanya menulis puisi tetapi juga berbagai tulisan lainnya. Namun, pada akhirnya ia lebih memilih untuk mendalami penerjemahan karya-karya sastra asing yang terkenal. Beberapa karya terjemahannya meliputi Citra karya Rabindranath Tagore (1943), Hantu dan Daniel Webster karya Stephen Vincent Benét (1950), Potong Rambut karya Ring Lardner (1950), Si Pirang Tegap karya Dorothy Parker (1951), Komedi Manusia karya William Saroyan (1952), Nasib Manusia karya Mikhail Sholokhov (1966), dan Negeri Salju karya Yasunari Kawabata (1972).
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Anas turut mendirikan dan menjadi redaktur Berita Indonesia, surat kabar pertama yang terbit di Jakarta pasca-proklamasi. Ketika pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta dan menjadikannya ibu kota pemerintahan, Anas bersama Usmar Ismail juga ikut hijrah ke sana. Di Yogyakarta, mereka mendirikan Arena, sebuah majalah yang berfokus pada kesusastraan. Anas turut berperan dalam penyelenggaraan Kongres Kebudayaan pertama yang digelar di Magelang pada tahun 1948, di tengah situasi revolusi yang masih berlangsung.
Setelah kembali dari Yogyakarta ke Jakarta, Anas bergabung dengan redaksi Balai Pustaka. Selain itu, ia juga menjabat sebagai sekretaris BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional). Namun, seiring perubahan status Balai Pustaka, Anas semakin fokus mengabdikan dirinya untuk kegiatan di BMKN.
Motor Penggerak BMKN
BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional) merupakan organisasi kebudayaan yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 dan dirampungkan melalui Konferensi Kebudayaan Indonesia tahun 1952. Sebelum BMKN berdiri, Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) telah lebih dahulu didirikan pada 1 Januari 1949 atas prakarsa Armijn Pane, Sunarjo Kolopaking, Sanjata Vidjaja, dan Wongsonegoro. Namun, peresmian LKI sempat tertunda akibat kondisi keamanan negara yang terganggu oleh agresi militer Belanda. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 dan pemerintahan kembali ke Jakarta, LKI akhirnya diresmikan pada 9 Maret 1950.
Dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi baru berbentuk "badan" yang kemudian diberi nama BMKN. Rancangan organisasi dan Anggaran Dasar BMKN disusun oleh Panitia Kesimpulan, yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Ki Mangunsarkoro, Dr. Bahder Djohan, dan Moh. Sjah, dan disahkan dalam Konferensi Kebudayaan Indonesia pada 12-14 April 1952. Setelah BMKN resmi berdiri, LKI melebur ke dalam badan ini pada 12 Mei 1952.
BMKN menghimpun keanggotaan dari berbagai latar belakang, seperti intelektual, sastrawan, jurnalis, pelukis, musisi, serta organisasi budaya dari berbagai wilayah Indonesia. Organisasi ini berfokus pada pengembangan kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi wadah inklusif dan beragam untuk memajukan kebudayaan nasional.
R Gaos Hardjasoemantri dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN sejak organisasi itu diresmikan. Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Bali, dan tahun 1960 di Bandung, namanya selalu diterima dengan aklamasi untuk tetap memimpin BMKN. Masa kepemimpinannya yang panjang akhirnya berakhir pada tahun 1965, setelah ia mengalami kecelakaan lalu lintas.
“Pada saat Gaos memimpin, Trisno Sumardjo dan Anas Ma'ruf merupakan motor penggerak organisasi BMKN,” tulis Buku Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok (Nunus Supardi, 2015: 88).
Pada masa menjelang dan selama peristiwa G30S/PKI, R. Gaos Hardjasoemantri bersama Anas Ma'ruf berperan aktif melindungi para seniman dan budayawan yang menjadi target, terutama mereka yang terlibat dalam penandatanganan Manifes Kebudayaan. Salah satu yang mereka bantu adalah penyair WS Rendra, yang karyanya ditolak berbagai media akibat afiliasinya. Dengan dukungan dari Trisno dan Sudjatmoko, Anas berhasil membantu Rendra mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat, sehingga ia tetap dapat berkarya meski dalam situasi yang penuh tekanan.
Sosok yang Disiplin
Ajip Rosidi menggambarkan Anas sebagai sosok yang sangat disiplin dan selalu berusaha menjaga kerapian serta keteraturan, sebuah sifat yang wajar dimiliki oleh seorang administrator. Namun, lingkungan kerja Anas yang dipenuhi para seniman dan budayawan, dengan ego besar dan kecenderungan menolak aturan, sering kali menimbulkan konflik. Ketegangan ini semakin memuncak pada masa sulit ketika penandatangan Manifes Kebudayaan menjadi target perburuan.
Meski Anas tidak terlibat sebagai penandatangan manifes, ia tetap berusaha membantu rekan-rekannya sembari menjaga keberlangsungan BMKN, organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya. Upaya ini, sayangnya, memunculkan tuduhan bahwa ia pengecut dari beberapa pihak. Keadaan semakin rumit setelah PKI dibubarkan pada tahun 1966 dan Lekra dilarang. Pada masa itu, seniman pendukung Manifes Kebudayaan merasa menjadi pemenang, sementara Anas kerap merasa kecewa atas tuduhan dari seniman dan sastrawan muda yang menganggapnya tidak turut berjuang melawan Lekra, sehingga tidak layak mendapat pengakuan atas kemenangan tersebut.
“Maka keberangkatannya ke Jepang, untuk mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia di Tokyo Gaidai tempat W.J.S. Purwadarminta pernah mengajar, merupakan jalan keluar baginya untuk menghindarkan ketegangan batin yang sangat menekan,” papar Ajip.
Malik Ibnu Zaman, kelahiran Tegal Jawa Tengah. Malik menulis sejumlah cerpen, puisi, resensi, dan esai yang tersebar di beberapa media online
Terpopuler
1
LBH Ansor Kendal Bahas Hak dan Kewajiban Banser dalam Diskusi Hukum Bersama Satkoryon Ngampel
2
Bawa Misi Sambung Sanad Hadis Ulama Indonesia-India, Ma’had Aly Tragung Batang Resmi Didirikan
3
Adab dan Akhlak Jadi Pondasi Utama dalam Pendidikan Santri
4
Presiden Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, 8.523 Kades dan Lurah se-Jateng Hadir di Klaten
5
Ahmad Zuhdi dan Wali Murid Selesaikan Persoalan secara Kekeluargaan, Uang Denda Ditolak Dikembalikan
6
Ansor Gabus Pati Ziarah ke Magelang, Perkuat Militansi dan Silaturahmi Kader
Terkini
Lihat Semua