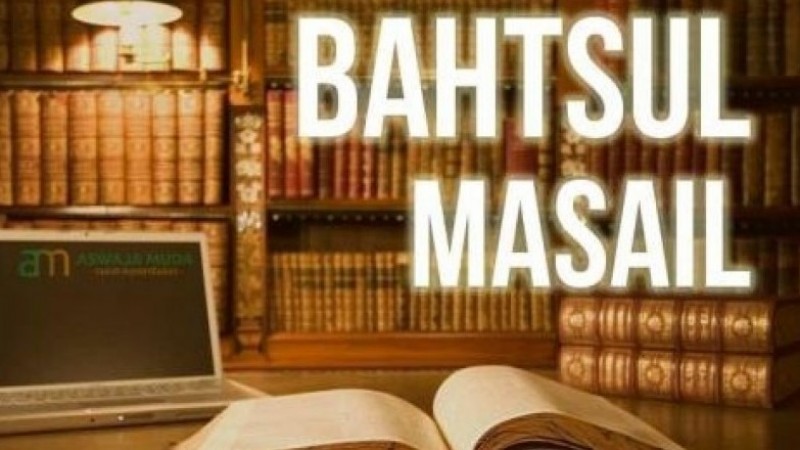Kontribusi Besar Lembaga Bahtsul Masail NU dalam Berbangsa dan Bernegara (1)
Ahad, 31 Oktober 2021 | 11:00 WIB
Pengantar Redaksi
Senin (1/11) Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Tengah akan menggelar kegiatan bahtsul masail membahas 3 masalah keagamaan di Kota Pekalongan. Untuk mengetahui peran dan kontribusi LBMNU dalam berbangsa dan bernegara, NU Online Jateng menurunkan tulisan yang dikutip tentang bahtsul masail oleh Imam Yahya Dosen UIN Walisongo Semarang, nu online, dan dari laman lbmnu.blogspot.com
Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail Diniyah merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (jamiyah), aktivitas bahtsul masail telah berlangsung sebagai praktik yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.
NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum bahtsul masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, belum diwadahi dalam organ tersendiri.
Pada tingkat nasional, bahtsul masail diselenggarakan bersamaan momentum kongres atau muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya Bahtsul Masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Muktamar I (1926) sampai Muktamar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan Bahtsul Masail yang menyertai Kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat-sendat tidak lagi tiap tahun.
tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan Bahtsul Masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa Muktamar yang dokumennya belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali Bahtsul Masail skala nasional yang menghasilkan 536 keputusan.
Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Muktamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen.
Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halaqah (sarasehan) di Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Harapannya, dapat mengonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan ijtihad jamai.
Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Muktamar 2004, status 'lajnah' ditingkatkan menjadi 'lembaga' sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU).
sejarah perjalanan bahsul masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauli tetapi secara manhaji. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.
Secara historis, pembahasan tentang konsep negara bangsa pernah dibahas para ulama pesantren dalam Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pergerakan nasional telah sejak lama dilakukan oleh kalangan pesantren, baik santri maupun kiai, termasuk menggembleng para pemuda untuk mencintai bangsanya.
Perjuangan ini lalu ditindaklanjuti oleh perjuangan para pemuda dalam meneguhkan negara berdasar asas kebangsaan. Peletakan negara bangsa (nation state) dilakukan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam catatan Abdul Mun’im DZ (Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011), gema Sumpah Pemuda Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia menggelora di seluruh penjuru Nusantara sehingga menjadi bahasan semua kalangan pergerakan termasuk dalam NU dan dunia pesantren secara umum.
Namun, salah satu butir yang menjadi perhatian adalah munculnya aspirasi negara bangsa sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Konsep negara bangsa tersebut sekaligus menjadi persoalan krusial bagi sebagian umat Islam yang masih berpandangan untuk mendirikan negara Islam. Karena persoalan ini menjadi bahan perbincangan umat Islam, maka sebagai bentuk tanggung jawab sosial, NU kemudian membawa persoalan tersebut ke dalam Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin.
Meskipun mayoritas masyarakat Nusantara beragama Islam, begitu pun tradisi dan budaya yang dikembangkan, bukan berarti di negeri Indonesia wajib didirikan negara Islam. Menurut para ulama NU, konsep negara bangsa yang digelorakan para pemuda tahun 1928 tidak lantas membatasi umat Islam di Indonesia. Dengan kata, nation state sudah sesuai dengan aspirasi Islam. Singkatnya, dalam Muktamar tahun 1936 tersebut, NU mempertegas bahwa nation state tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, juga sudah memenuhi aspirasi umat Islam. Karena di dalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengajarkan dan menjalankan agamanya secara bebas. Dengan demikian, Islam tidak perlu membuat negara lain yang berdasarkan syariat Islam, karena negara yang dirumuskan (negara bangsa) telah memenuhi aspirasi Islam.
Pembahasan negara bangsa dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Karena nilai-nilai tersebut termaktub di dalam sila-sila dalam Pancasila. Indonesia memang mayoritas penduduk memeluk ajaran Islam. Kuantitas tersebut tidak lantas bahwa di Indonesia wajib didirikan negara Islam. Karena bentuk negara bangsa berdasarkan Pancasila telah memenuhi aspirasi Islam, baik dalam muamalah maupun dalam perundang-undangan. Kala itu, NU yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy’ari ini menolak gagasan Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam karena pertimbangan historis dan kebangsaan. Pendirian negara Islam juga tidak mempunyai pijakan syariat karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Lagipula, Indonesia merupakan kumpulan bangsa majemuk yang sedang berusaha secara bersama-sama dalam berjuang mencapai kemerdekaan. Sikap tegas NU terkait darul Islam dibahas melalui Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ini menunjukkan bahwa ketegasan NU menolak Darul Islam Kartosoewirjo mempunyai dasar, tidak dilakukan secara srampangan. Hal ini juga menggambarkan bahwa para ulama NU selalu mendasarkan diri dengan pijakan syariat. Apalagi konsep negara bangsa sama sekali tidak mengekang agama Islam sehingga negara bangsa merupakan perwujudan aspirasi Islam.

Arti Darul Islam
Menurut Salah seorang ulama NU, KH Achmad Siddiq (1926-1991) memberikan penjelasan terkait Darul Islam yang dibahas dalam Muktamar NU 1936 di Banjarmasin. NU mengakui Darul Islam dalam artian bahwa di wilayah Nusantara pernah hidup kerajaan-kerajaan Islam. Namun, umat Islam saat itu hidup lestari dengan umat agama lain sehingga Islam adalah sistem nilai, bukan sistem negara. KH Achmad Siddiq menegaskan, pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU 1936 tersebut bukan tanpa dasar. Kata Darul Islam bukanlah sistem politik atau ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam) yang lebih tepat diterjemahkan wilayatul Islam (daerah Islam), bukan negara Islam. (Abdul Mun’im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011).
Persoalan ini kemudian dipertegas oleh ulama dari Situbondo, Jawa Timur, KH Afifuddin Muhajir dalam Bahtsul Masail Maudluiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat. Kiai Afifuddin menegaskan bahwa harus dibedakan antara istilah Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Darul Islam merujuk pada wilayah Islam dengan masyarakat yang berupaya mempraktikkan nilai-nilai Islam secara universal, sedangkan Daulah Islamiyah ialah konsep yang mempunyai tujuan-tujuan politik kekuasaan.
Adapun dalam Muktamar NU 1936, motif utama dirumuskannya pendapat bahwa Darul Islam merupakan wilayah Islam ialah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang tidak jelas non-Muslim, maka harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya, termasuk menentang ketidakperikemanusiaan penjajah. Sebab itu, NU menolak ikut milisi Hindia-Belanda karena menurut Islam, membantu penjajah hukumnya haram. Bahkan untuk membangun masyarakat Islam, setiap penjajahan harus disingkirkan. Keteguhan pendirian NU terhadap bentuk negara bangsa ini kembali dibuktikan saat pertama kali datang Laksamana Maeda, pimpinan tertinggi tentara Jepang pada 1943. Maeda menanyakan siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi negeri ini untuk diajak berunding dengan Jepang. Dengan tegas KH Hasyim Asy’ari menjawab bahwa yang pantas memimpin bangsa ini ke depan ialah Soekarno, seorang tokoh nasionalis terkemuka.
Untuk itu, ketika Indonesia merdeka pada 1945, pemimpin tertinggi NU tersebut merestui Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pancasila Pondasi Kokoh Negara Bangsa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq (Menghidupkan Kembali Ruh Pemikiran KH Achmad Siddiq, 1999) bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Karena hal itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. (bersambung)
Editor: M Ngisom Al-Barony
Terpopuler
1
NU Pati Keluarkan Maklumat Jelang Aksi 13 Agustus
2
Kiai Mustain Nasoha Khatamkan Kitab Minahul Qudsiyah, Lanjutkan Kajian ke Sirojut Thalibin
3
Satlantas Pati Siapkan Rekayasa Lalin, Ribuan Personel Kawal Aksi 13 Agustus
4
Yaaqawiyyu Jatinom: Warisan Ulama, Perekat Umat, dan Syiar Islam Nusantara
5
Seminar Fiqih Kewanitaan, LBM PCNU Purworejo Bekali Kader Perempuan NU Loano Pengetahuan Fardhu Ain
6
Sejarah Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
Terkini
Lihat Semua