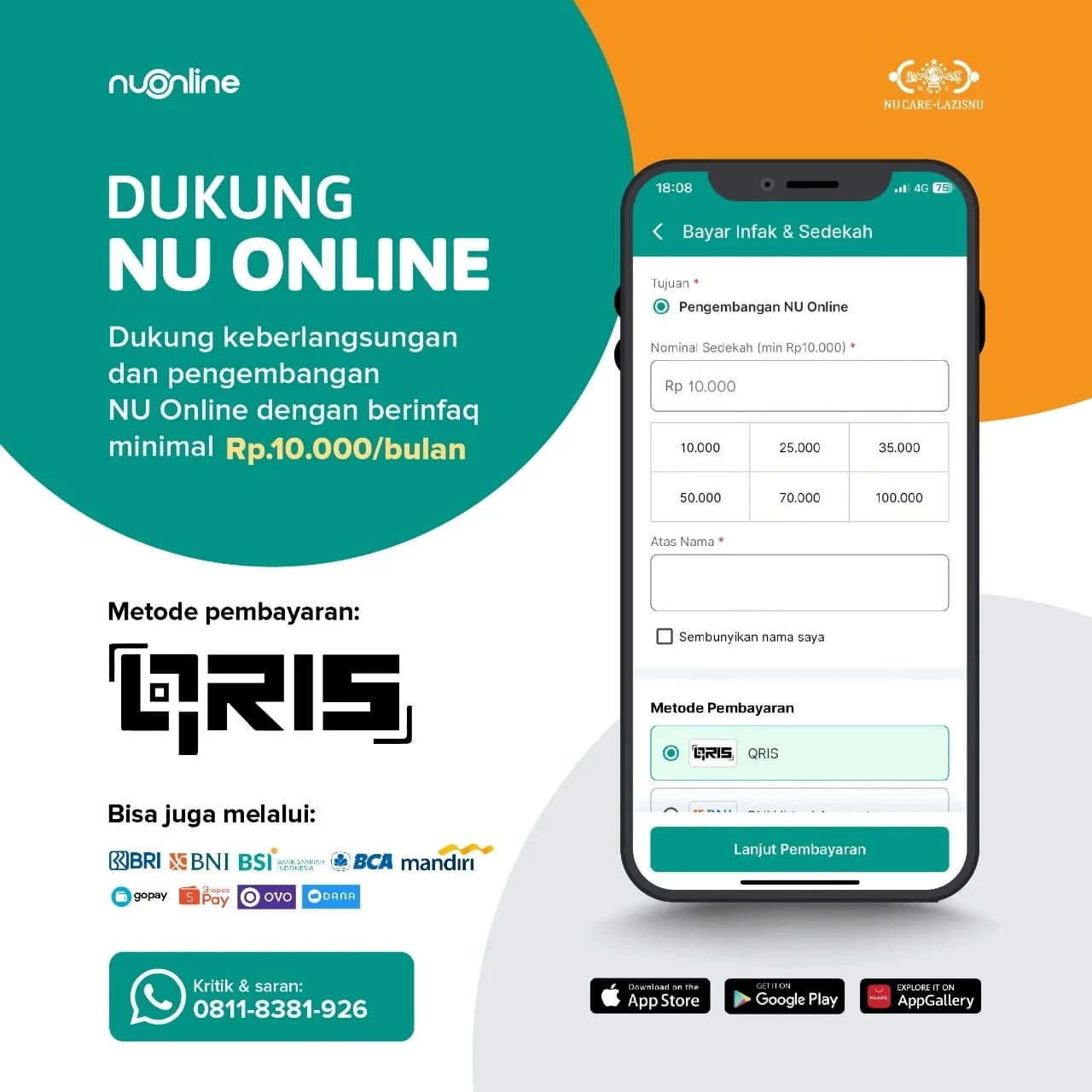Puasa Tasu’a dan ‘Asyura: Antara warisan kenabian dan Peneguhan Syariat Islam
Kamis, 3 Juli 2025 | 16:00 WIB
Islam adalah agama yang menekankan identitas dan otoritas syariatnya, namun tetap memberi ruang penghargaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang pernah ada dalam tradisi sebelumnya. Dalam konteks ini, puasa Tasu’a (9 Muharram) dan ‘Asyura (10 Muharram) menjadi contoh nyata bagaimana Islam mengadopsi nilai luhur yang dilakukan oleh umat terdahulu, namun dengan sentuhan pembeda sebagai penegas otoritas syariat Islam.
Latar Sejarah Puasa Tasu’a & ‘Asyura
Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mereka menjelaskan bahwa hari itu adalah hari di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa AS dan Bani Israil dari kejaran Fir’aun. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Musa AS pun berpuasa pada hari tersebut. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda:
Baca Juga
Bulan Muharram, Gak Boleh Nikah?
نَحْنُ أَوْلَى بمُوسَى مِنكُم فأمَرَ بصَوْمِهِ
“Kami (kaum muslimin) lebih berhak atas Musa daripada kalian” (HR. Muslim, no 1130)
Setelah melihat praktik puasa Yahudi tersebut, Rasulullah tidak serta merta meninggalkan kebiasaan baik yang telah mereka lakukan. Sebaliknya, Rasul justru menganjurkan umatnya untuk ikut berpuasa.
Sebagaimana ahli hikmah berkata:
ٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَبْقَى صَالِحًا وَلَوْ صَدَرَ مِنْ فَاجِرٍ
"Amal yang baik tetaplah baik, meskipun datang dari orang jahat."
Selain anjuran untuk berpuasa ‘Asyura, Rasulullah juga berusaha untuk menyelisihi daripada perbuatan orang-orang Yahudi dengan menambahkan puasa sehari sebelumnya yaitu puasa Tasu’a (9 muharram).
Rasulullah bersabda:
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ
“Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa juga pada hari kesembilan (Tasu’a)." (HR. Muslim, no 1134)
Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menolak kebaikan yang dilakukan oleh kaum terdahulu, tetapi tetap berusaha menegaskan perbedaan (ikhtilaf) agar Islam tampak sebagai syariat yang independen dan tidak bergantung secara simbolik kepada tradisi mereka.
Dalam ilmu ushul fikih dan kaidah syariat terdapat prinsip:
المُخَالَفَةُ لِلْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى مَقْصُوْدَةٌ شَرْعًا
“Penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani adalah tujuan syar’i yang diinginkan”
Kaidah ini didasarkan pada banyak praktik Nabi yang menyelisihi umat terdahulu dalam hal ibadah, penampilan, dan tradisi, seperti: menyelisihi cara puasa mereka dengan menambahkan satu hari sebelumnya (Tasu’a), menyelisihi arah kiblat (berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka’bah) dan menyelisihi cara berpakaian, potong kuku, dan kebersihan diri.
Tujuannya adalah menjaga distingsi (tamayyuz) syariat Islam sebagai syariat yang berdiri sendiri, sempurna, dan berbeda dari agama-agama sebelumnya, meskipun tetap mengakui esensi kebenaran nabi-nabi terdahulu. Wallohu a’lam.